"SUDAH kau putuskan?"
"Sudah," ujar Rahim sambil menggeleng. Lelaki itu terus memandang kosong selembar undangan yang terletak di atas meja rotan.
"Dia minta kesediaanmu untuk menjadi saksi pada pernikahan anaknya. Sebagai saudara, harusnya kau penuhi,"saran Sophia, istri Rahim.
"Justru itu. Aku kenal dia. Dia…. Busuk!"ketus Rahim sambil beringsut dan melempar pandang ke halaman. Sophia, hanya bisa mengelus dada. Dia tak paham betul alasan kedua sedarah serahim itu bermusuhan, selama lebih duapuluh tahun.
"Aku begini, karena ulahnya. Apa itu yang dinamakan saudara? apa itu yang disebut keluarga? Aku tak bisa menerima itu. Meski dua puluhtahun aku puasa dan sengaja tak mau tahu lagi apa yang diperbuatnya. Biar saja, dia mengurus hidupnya," ujar Rahim, lelaki lima puluh tahunan itu beranjak bangkit dan meninggalkan Sophia yang termangu sendiri di teras.
"Oke, baik! Terserah saja. Kau datang atau tidak, tapi aku akan datang, aku menghormati abangmu!"
"Oh, begitu? Jadi kau lebih memilih datang dan tak memperhitungkan perasaanku? Baik. Baik!" Rahim mengambil kunci mobil dan seberapa lama kemudian, mesin menyala. Rahim dan mobilnya menghilang dari pandangan Sophia.
Di balik setirnya, Rahim sedang berperang. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin, Sophia yang sudah dinikahinya selama duapuluhlima tahun belum juga bisa meraba perasaan dan kedalaman hatinya. Rahim kecewa. Gas diinjak, Rahim memasuki sebuah jalan. Jalan yang pernah dilaluinya, bersama Rahman.
***
"Ini bukan sekadar pilihan, Him. Ini sebuah keharusan. Keharusan yang akan kita ambil untuk mencapai perubahan nasib. Aku sudah muak dengan kekalahan ini. Aku berniat merubahnya, dan aku merubahnya,"ujar Rahman. Rahim berang. Dia tak menyangka Rahman akan tega berkhianat dari ideologi yang sudah dianutnya sejak orok.
"Tapi partai itu dan tentara lah yang menyebabkan kematian Abu. Kau tak ingat atau sengaja tak mau mengingatnya?" kata Rahim. Bergidik segenap bulunya ketika mengingat peristiwa penghilangan nyawa Abu.
"Apalah artinya kehilangan Abu, atau dua, atau tiga, atau seribu Abu? Ini politik. Kita tak sedang membalas dendam. Ada banyak waktu untuk membalas. Sekarang, bagaimana caranya kita bahu membahu memenangkan partai ini, dan mengubur masa lalu kita untuk kemudian berdiri menghadap jalan terang benderang demi masa kejayaan di masa datang,"
"Gila kau!"
"Kau yang gila, tak mau melihat kenyataan! Kalau kau berpikir untuk ikut partai fusi itu, maka siaplah untuk membaca sejarahmu yang selalu salah dan kalah!"
"Aku semakin tak mengenalmu,"
"Sama! Aku pun tak tahu hal bodoh apa yang kau pikirkan!"
"Baik. Mulai sekarang, kita tak saling kenal!" Rahim memukul stirnya! Mendadak mobilnya berhenti.
***
Dering nada panggil menyadarkan Rahim dari lamunan.
"Halo Pak, selamat siang," ujar Rahim beramah tamah pada orang di seberang telepon. Mobil kembali melaju dengan kecepatan yang pelan. Kepalanya berat.
"Aku semakin tak paham dengan politik sekarang," ujar dia kepada diri sendri. Sesekali digeleng-gelengkannya kepalanya. "Kemarin berkoalisi dengan partai A, beberapa jam kemudian, diputuskan hubungan itu dan memilih bergabung dengan Partai T. Dilalah, sekarang, majelis sedang memikirkan kemungkinan untuk berjuang bersama Partai B. Partai B?!" ulang Rahim setengah berteriak. "Setan alas!" dia memaki. Diam sejenak, kemudian dia memacu mobilnya lagi, melewati jalan, yang dulu biasa dilewatinya bersama Rahman.
***
Partai B adalah partai yang bertanggung jawab atas kematian Abu. Partai itu pula yang menjadi garda terdepan untuk memberangus dan membantai hak politik atau nyawa kader-simpatisan partai yang dinaungi Abu, lebih duapuluh tahun yang lalu.
Rahman dan Rahim terpaksa terbuang ke jalanan. Mengais hidup di bawah tekanan politik Partai B yang berkuasa sejak kejatuhan rezim Orde Lama. Partai itu pula yang sudah mengebiri kadar kemanusiaan Rahman, abangnya. Rahim tak paham, sekenario apa dibalik pertentangan idiologi yang dimilikinya dengan sang abang.
"Aku lelah berdiri seharian di jalanan,"
"Tapi partai itu yang membunuh Abu,"
"Bukan partainya, tapi orang-orang yang membuat kebijakan di partai itu,"
"Tidak! Sama saja! Idiologi palsu mereka adalah sumber segalanya,"
"Itulah politik, semua bisa benar, semua bisa samar. Semua pun bisa cemar,"
"Pelacur!"
"Tidak,"
"Iya, kau menjual murah marwahmu di depan adikmu,"
"Kau akan paham suatu hari nanti,"
"Kalau begitu, aku menentangmu,"
"Silakan,"
"Aku akan mengabdikan kemampuanku pada partai oposisi,"
"Begitukah? Oposisi sampai mati?"
"Asli, oposisi sampai mati. Bukan seperti kau, pelacur idologi,"
Akhirnya, 20 tahun lalu, Rahman dan Rahim memutuskan berpisah di jalan. Rahman masuk Partai B. dan Rahim masuk Partai D, sebuah partai bentukan Orde Baru yang merupakan hasil fusi beberapa partai yang pahamnya dianut Abu. Selama 20 tahun itu. Keduanya melintasi jalan masing-masing. Berpapasan namun tak saling sapa. Melihat tapi tapi tak saling menyadari kehadiran masing-masing.
***
Rahim terus memacu mobilnya di jalur jalan kenangan. Dia melihat dirinya duapuluh tahun lalu ditendang polisi ke balik jeruji. Dia melihat dirinya menggelar aksi di depan istana. Dia melihat dirinya direkrut Partai D sebagai sekretaris. Dia melihat kesuksesan demi kesuksesannya bersama partai D. Dia melihat dirinya dibuang dari kursi strategis di Partai. Dia melihat dirinya kalah bersaingan dengan anggota baru. Dia melihat dirinya menikahi Sophia. Dia melihat… Rahman selalu hadir dalam setiap duka dan kesuksesannya. Dia melihat Rahman ada di sana!
Rahim kesal. Namun dia terus berpikir untuk meneruskan jalannya sendiri. Maka dipacunya mobil semakin laju, lurus menjurus ke kantor pusat Partai D.
Telepon genggamnya berdering lagi.
"Gimana perkembangan?"
"87 persen suara sepakat untuk berkoalisi dengan Partai B..."
"Bagaimana mungkin, saya masih di jalan..."
"Secara aklamasi..."
"Tetap tak bisa, ketua mesti mendengar penjelasan saya. Dia mesti menghitung loyalitas saya,"
"Hari begini, semua orang lebih memilih Jaguar ketimbang loyalitas,"
"Sampeyan tidak merasionalkan kebijakan itu,"
"Tak terbendung, Bung, saya walkout..."
Mendidih darah Rahim. Dibantingnya setir ke kiri. Dilihatnya Rahman tertawa di luar jendela. Prang! Suara pecahan kaca menyusul. Rahim terlelap dalam genangan kenangan…
***
"Dimanapun kau berada, aku akan selalu mengawasimu,"
"Dimanapun?"
"Iya."
"Kalau aku sembunyi di dalam gua, bagaimana?"
"Aku pasti bisa menemukanmu…"
"Kenapa kau selalu mau menemukanku?"
"Karena aku abangmu. Aku akan menjagamu..."
"Kau akan menjagaku dari apa saja?"
"Iya,"
"Termasuk para pembunuh Abu?"
"Tentu dan itu pasti…"
***
Hari keempat. Rahim membuka matanya. Dirasakannya ada yang hilang dari tubuhnya. Diliriknya infuse yang masih tertancap di kulit tangannya. Dia melempar senyum pada Sophia yang duduk di sampingnya.
"Sayang..." bisik Sophia.
Rahim mengangguk. Diedarkannya matanya ke seluruh ruangan. Tatapnya berhenti di sebuah sudut. Samar-samar dia menangkap bayangan. Itu bayangan Rahman. Bayangan yang selama ini dibencinya. Bayangan yang selalu menghantuinya. Bayangan yang selalu dengan keras dihindarinya. Bayangan yang selalu dirinduinya.
Bayangan itu mendekat. Semakin jelaslah, bahwa itu Rahman.
"Sejahat apapun aku, kau tetap adikku. Sebodoh apapun kau, aku tetap abangmu. Mungkin itulah kutukan kita. Sekarang istirahatlah dulu adikku. Pulihkan semua lukamu. Termasuk dari Abu dan dari aku,"ujar Rahman dengan senyum ditahan.
"Sontoloyo kau! Kau selalu bisa menemukanku..." kata Rahim sambil tertawa.
Keduanya menghapus dendam masa silam. Kedua abang-adik itu bercengkrama ramah. Hanya mereka berdua saja. Rahim tak peduli dengan kehadiran Sophia, dia tak peduli dengan kehilangan kaki kirinya. Dia tak peduli dengan Partai B atau Partai D. Dia hanya peduli, bahwa dia telah pulang ke rumah. Dan menemukan semua perabotan masih utuh dan berada pada tempatnya.
Binjai 7 Feb. 2010

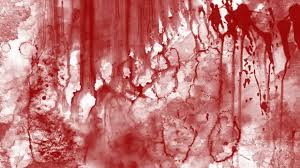













KOMENTAR ANDA