ORANG-orang bilang, sekarang era informasi. Saya bilang juga, iya. Informasi kian tumpah ruah. Datang darimana saja. Beragam sumber dan media penyampaian. Kita pun bisa mengaksesnya. Kapan suka, kapan mau. Tapi kalau orang-orang bilang, sekarang era keterbukaan informasi. Saya bilang, nanti dulu.
Keterbukaan informasi mengisyaratkan ketiadaan ketertutupan. Informasi yang disampaikan apa adanya. Seperti rekaman video sebuah peristiwa yang ditayangkan dari A sampai Z. Detil kronologis kejadian tidak ada luput. Biar barang sedetik pun. Begini baru namanya terbuka. Tapi apa mungkin? Praktiknya, informasi yang sampai kepada kita tidak utuh. Peristiwa keseluruhan dipotong bagian per bagian. Dibuatkan pembingkaian sedemikian rupa. Demi alasan redaksional, durasi waktu, dan kepentingan politik-bisnis si penyampai informasi. Malahan sering informasi yang sampai ke kita berbentuk kesimpulan. Bukan lagi informasi awal yang seyogianya menginformasikan peristiwa. Ternyata, informasi yang sampai ke kita sudah dipilah-pilih dulu entah oleh siapa.
Dunia pendidikan formal kita pun tak jauh beda. Para siswa dididik untuk memilih pilihan semu. Seakan-akan memilih padahal tidak memilih sama sekali. Contohnya, di Ujian Nasional (UN). Satu soal pertanyaan di UN telah disediakan beberapa pilihan jawaban berganda. Di luar pilihan jawaban itu, tak ada. Siswa diharuskan memilih dari yang disediakan. Mulai dari soal sampai pada jawaban telah dipilah-pilih dulu entah oleh siapa.
Apa yang saya sampaikan ini cuma contoh kecil saja. Gambaran tentang bagaimana kehidupan kita yang 'seolah-olah'. Seolah-olah memilih. Memilih atas dasar kesadaran diri. Padahal, sekali lagi, sekedar 'seolah-olah' saja. Pilihannya telah disediakan tanpa ada alternatif lain. Disediakan setelah dipilah-pilih untuk kita pilih. Dipilah-pilih dulu entah oleh siapa.
Wajar jika kita merasa khawatir. Ternyata, sedari usia dini alam pikiran kita telah dikonstruksi sedemikian rupa. Pikiran yang selayaknya menjadi prerogatif sendiri malah telah digiring ke arah kepalsuan. Implikasinya, kesadaran kita tentang hak dan kewajiban jadi samar-samar. Kita melunasi kewajiban tapi hak justru tersendat. Sebuah kondisi yang dinikmati para pemilik kuasa politik dan ekonomi. Wah, sayang sekali.
Di balik semua, saya masih percaya kita bisa membuat pilihan sendiri. Syarat utamanya adalah pengakuan. Mengakui sepenuh diri bahwa pilihan masih bisa diciptakan. Menciptakan kemandirian ruang sosial yang di dalamnya pilihan pasti selalu ada. Dimulai dari ruang terdekat di kehidupan sendiri. Keluarga, misalnya. Berusaha menjauh dari berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Sikap berlebihan atau ekstrim, mau tidak mau, dengan cepat akan membusukkan diri sendiri. Itu pasti. Lihat sajalah.
*Praktisi Simbol & Meditasi


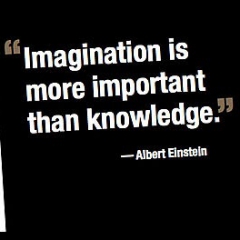












KOMENTAR ANDA